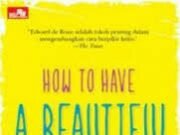|
IKLAN
loading...
|

“Alhamdulillah, sekarang sekolah di kampung kami sudah gratis, anak-anak sudah mulai sekolah lagi. Perdamaian sangat berpengaruh bagi kami,” ujarnya.
Sang surya mulai tampak di pojok langit setelah pagi. Teriknya mulai menerobos masuk ke dalam rumah berdinding rumbia dan beralas bambu itu. Jaraknya hampir tak terlihat dari sisi jalan yang penuh kerikil, juga hutan kecil yang menutupi pandangan mata. Di situlah Nuraini Ibrahim, 40 tahun, janda korban konflik Aceh tinggal bersama tujuh anaknya.
Sosok wanita paruh baya itu terlihat disana. Dia terlihat cekatan melepaskan tali yang mengikat karung-karung padi. Diserakkannya padi-padi itu di atas terpal biru yang penuh dengan tambalan. Dia panaskan padinya di bawah terik matahari terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pabrik untuk diolah menjadi beras.
Setelah membereskan semuanya, Nuraini menitipkan padi yang telah dijemur tadi pada anaknya agar tak dimakan ayam. Dengan tergopoh-gopoh wanita itu menuju ke sawah. Maklum saja, sejak ditinggal sang suami, Jufri bin Mahmud, enam tahun silam, semua kebutuhan keluarga harus ditanggungnya sendiri.
“Anak saya masih kecil-kecil. Untuk kebutuhan keluarga sehari-hari saya mencari upah di sawah, itupun pada musim turun ke sawah saja,” sebut Nuraini, dengan menahan tangis menceritakan kehidupannya.
Dalam sehari Nuraini mampu mengumpulkan uang Rp 30.000 – 50.000, sebagai upah hasil bekerja di sawah. Tak jarang upah itu akan diterimanya pada saat musim panen tiba.
“Kalau uang jarang saya terima. Di sini sistemnya setelah panen baru kita dibayar dengan padi,” ujarnya.
Di ujung perempatan jalan Nuraini telah ditunggu oleh rekan-rekan seprofesinya. Di sana juga ada janda inong balee lainnya. “Mereka adalah Lawiyah Ismail, Zainabun, Nyakcek binti Harun dan Lawati Abubakar,’’ kata Hamzah Yacob, Geusyik Desa Kumbang, Metareum, Pidie. Mereka pergi menanam bibit padi di sawah salah satu warga desa tersebut.
Desa yang terletak di kaki gunung ini memiliki 674 jiwa penduduk. Lima orang di antaranya merupakan janda korban konflik. Saat konflik berkecamuk di Aceh, delapan warga desa ini meninggal dan 11 lainya mendapatkan kekerasan fisik oleh aparat keamanan yang berpatroli saat itu.
Iringan awan merah di langit mulai menelan teriknya matahari sore, menjelang magrib. Dia pulang dengan peluh menyelimuti tubuhnya. Wanita yang penuh senyum itu masih terlihat ramah.
Nuraini masih teringat ketika tengah malam dia dibangunkan oleh orang bersenjata yang menanyai keberadaan suaminya. “Di mana suamimu?! Ngaku atau kalau nggak saya tembak!” ujarnya menirukan perintah tentara yang membuat nyalinya kecut. “Sudah naik ke gunung, pak,’’ jawab Nuraini dengan nada gemetar. Melihat rumahnya dipenuhi aparat keamanan, anak-anaknya menangis ketakutan.
“Setelah mareka membentak-bantak saya sekitar satu jam, mereka mulai kesal. Akhirnya mareka pergi meninggalkan rumah saya. Namun salah seorang dari mereka sempat menendang saya,’’ kenang janda yang memiliki tujuh anak ini.
Setelah peristiwa itu, Nuraini selalu dihantui rasa ketakutan. Berbagai macam teror sering dirasakan. Untuk meninggalkan kampungnya tak mungkin, dia tak tahu harus kemana. “Jangankan untuk biaya hidup di rantau, untuk ongkos pun saya tak punya,” tutur Nuraini.
Kesedihan terus dirasakan Nuraini. Dia menyandang status janda ketika sedang mengandung putri sulungnya empat bulan. Suaminya Jufri, tewas dalam perjalanan membawa pulang daging meugang untuk keluarga menjelang lebaran.
Kemeriahan lebaran seakan tercoreng di benak Nuraini dan anak-anaknya, suami dan ayah mereka pergi untuk selamanya, rasa kehilangan masih membekas dalam ingatan mereka. “Abang (suami –red) ditembak di belakang rumah menjelang subuh,” ujar Nuraini berurai air mata.
Nuraini harus berjuang menghidupi tujuh orang anaknya. Kesehariannya diisi dengan bertani dan berladang seperti halnya masyarakat Desa Kumbang lainnya. Tak satupun anak-anaknya yang sekolah. Keterbatasan ekonomi dan kondisi keamanan menjadi kendala saat itu.
Setelah damai Aceh pada 15 Agustus 2005 lalu, pintu kemudahan mulai terbuka. Nuraini mulai merasakan banyak perubahan dalam kehidupannya. Walau harus hidup tanpa suami. Nuraini ingin menghapus lembaran pahit masa lalunya.
“Alhamdulillah, sekarang sekolah di kampung kami sudah gratis, anak-anak sudah mulai sekolah lagi. Perdamaian sangat berpengaruh bagi kami,” ujarnya.
Nuraini tak ingin anak-anak mengikuti jejaknya. Dia berharap anaknya kelak bisa menjadi orang yang berguna. Untuk biaya pakaian dan perlengkapan sekolah anak-anaknya kini memperoleh bantuan beasiswa dari Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA). “Anak-anak dapat beasiswa sebesar sejuta enam ratus ribu setiap orang, tapi anak saya yang bungsu tak dapat,’’ sebut Nuraini.
Tercatat sebagai janda korban konflik, Nuraini juga mendapatkan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat dari BRDA Kabupaten Pidie sebesar Rp. 9.000.000. Dana itu diberikan sebagai modal usaha.
“Seharusnya dana bantuan itu sepuluh juta. Tapi uangnya dipotong sejuta oleh pengurus setempat. Katanya, untuk biaya administrasi. Begitu juga dengan bantuan diyat (bantuan bagi korban konflik -red) yang seharusnya tiga juta, tapi saya hanya menerima dua juta lima ratus ribu,’’ ujarnya.
Wakil Ketua BRDA Kabupaten Pidie, Husni Ismail menuturkan bahwa terdapat 1.500 janda korban konflik di Pidie. Dari jumlah itu, 1.314 telah mendapatkan bantuan dana diyat sebesar Rp. 3.000.000 per jiwa.
“BRDA juga telah mengucurkan dana bantuan pemberdayaan ekonomi untuk para janda korban konflik. Mereka bisa mengambil uangnya yang telah disalurkan melalui sebuah Bank berjumlah sepuluh juta per keluarga,” ungkap Husni.
Perhatian terhadap janda korban konflik juga datang dari Komite Peralihan Aceh (KPA) Kecamatan Mila. Namun, bantuan dari KPA hanya dilakukan pada musim-musim tertentu.
“Setiap meugang dan lebaran, KPA selalu membantu janda inong balee dan anak-anaknya,’’ ujar Muhammad Jakfar, Ketua KPA Wilayah Mila.
.Dana konpensasi dari pemerintah tidak membuat hati Nuraini lega. Dengan kondisi rumahnya saat ini yang berukuran 4×4 cm, berbalut dinding rumbia dan beralas bambu terlihat semakin rapuh dimakan rayap. “Kalau malam, anginnya menerobos masuk, membuat saya dan anak-anak mengigil. semoga ada yang berkenan memberi saya bantuan rumah” ungkapnya dengan nada iba.
Nasib serupa juga dialami janda korban konflik lain di Desa Kumbang, Metareum. Lawiyah Ismail, 45 tahun, hingga saat ini masih merasakan trauma akibat rumahnya sering didatangi pria bersenjata pada malam hari untuk menayakan perihal keberadaan suaminya, Muslim yang saat itu salah seorang orang yang paling dicari di desa itu.
Rasa takut yang terus menghantuinya, tepat pada tahun 2002, dengan modal dari hasil menjual sepetak sawah dan seekor sapi, Lawiyah yang saat itu dalam kondisi hamil muda berangkat bersama anak pertamanya meninggalkan kampung halaman. ‘‘Dua bulan saya di Medan, saya mendapat kabar kalau suami saya sudah meninggal,” ujar Lawiyah dengan mata berlinang.
Dengan perasaan duka dan kesedihan mendalam, Lawiyah berniat kembali ke Aceh untuk melihat wajah suaminya yang terakhir kali. Tapi karena keadaan Aceh yang semakin parah, dengan terpaksa dia membatalkan niat itu. Kesedihan diratapinya jauh dalam perantauan.
Lawiyah melahirkan anak keduanya di Medan. Dia kembali lagi ke kampung halamanya setelah Aceh damai. Kini, dia mulai menata hidupnya kembali. Semua harta peninggalan suaminya berupa sepetak sawah dan seekor sapi telah ia jual. “Setelah kembali ke kampung, saya tak punya apa-apa lagi. Untuk makan saja, saya harus minta pada ibu dan saudara saya,’’ sebutnya.
Selain bekerja dalam tekanan, Lawiyah masih mencurahkan penuh kasih sayang untuk kedua anaknya. Dia terlihat tegar di hadapan anak-anaknya yang mulai tumbuh. Namun Lawiyah tetap tak bisa menutupi kekurangannya, hingga kini dia tak memiliki rumah sendiri, dia hanya menumpang di rumah ibunya yang terasa sempit oleh ukurannya. “Kalau sekarang ada uang bantuan dari BRDA untuk pemberdayaan ekonomi. Tapi bagaimana jika anak-anak saya bersekolah nanti?” katanya.
Meski masa lalu suram, Nuraini dan Lawiyah tetap memiliki tekad juang yang tinggi. Mereka tak hanya berharap semata. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya karena hidup akan terus berputar. Nuraini, Lawiyah dan janda inong balee korban konflik lainnya juga ingin merangkul harapan-harapan mereka yang tertunda. Harapannya sebagai seorang ibu, dan juga harapan janda inong balee di Metareum, Pidie. [Ferdian A Majni]