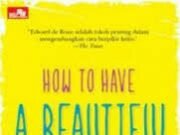Aang Ananda Suherman*

Banda Aceh – Ia sangat paham bila diajak bicara sejarah, HAM, perempuan, dan politik Aceh. Ia mengulas gerakan pemisahan diri di Aceh, Papua, Timor Timur. Menurutnya, nasionalisme kita sudah beda.
Ia Otto Syamsuddin Ishak. Otto lahir di Aceh, Oktober 1959. Kini ia dosen Sosiologi di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan tim peneliti Imparsial. Imparsial adalah lembaga non pemerintah yang menyelidiki dan mengawasi berbagai pelanggaran HAM di Indonesia. Didirikan oleh Otto, Munir dan 16 pekerja HAM lainnya pada Juni 2002. Ia juga ikut keluar masuk hutan saat Daerah Operasi Militer di Aceh.
|
IKLAN
loading...
|
Saat DOM diterapkan, tercatat 8.344 korban sipil di Aceh. “Kami mendampingi dan mengadvokasi hak-hak sipil mereka,” ungkap Otto. Aktivitasnya sampai ke dunia internasional saat diundang SubKomisi Hak Asasi Manusia PBB di Geneva pada 1999.
Hari itu Otto terlihat santai dengan jins dan kemeja lengan pendek. Ia mengampu kursus Jurnalisme Investigatif yang ditaja Yayasan Pantau Jakarta—dulu menerbitkan majalah Pantau yang concern memantau mutu jurnalisme di Indonesia—Juni 2011.
Kru Bahana, Aang Ananda Suherman, berbincang bersama Otto Syamsuddin Ishak seputar gerakan pemisahan diri; di Aceh, Papua, dan Timor Timur. Berikut petikannya.
Apa arti nasionalisme bagi Anda?
KeIndonesiaan itu kan pengalaman bersama pada zaman kolonial. Saat Indonesia merdeka, nasionalisme anti kolonial tak ada musuh lagi. Lalu ketika pemerintah tak mampu menampung aspirasi masyarakat Indonesia, terutama di luar Jawa, maka pengalaman bersama sesudah kolonial terasa beda.
Misal, orang Sumatera lihat Jawa kok makmur. Jalannya bagus. Juga orang Papua lihat kehidupan di Jawa lebih baik, padahal hasil alam Papua banyak diambil.
Itu jadi faktor utama mereka lihat kembali komunitas politik lama mereka, seperti romantisme sejarah lah.
Orang Aceh lihat masa kesultanan Aceh dulu yang hebat. Bisa terkenal ke seluruh dunia, ketika berada dalam pemerintahan Indonesia seperti dalam tempurung. Orang Riau juga begitu, beromantisme dengan sejarah masa lalu.
Kemudian romantisme sejarah itu tercampur dengan sentimen etnis. Etnisitas bila berbenturan dengan politik, ditambah perbedaan etnis, muncullah kasus. Saya kira begitu.
Apakah gerakan pro kemerdekaan Aceh sudah mati sama sekali?
Itu masih. Ia akan selalu berproses, bukan Aceh saja, tapi seluruh Indonesia. Sekarang malah ada faktor politik desentralisasi. Daerah mulai cari identitas. Ke-Aceh-an, ke-Melayu-an, ke-Papua-an, ke-Bugis-an, dan seterusnya. Itu akan dicari lagi karena orang butuh identitas. Ketika dia masuk ke identitas Indonesia yang begitu besar, mereka tenggelam.
Jadi dalam tempurung Indonesia sebenarnya ada pertemuan antar etnis. Tapi dalam sistem politik otoritarian masa lalu, maunya menyebut kita ini Indonesia, kan tidak bisa. Karena kita berasal dari daerah masing-masing.
Terjadi pemberontakan apakah memang ketidak adilan pusat?
Kenyataannya begitu kan? Misal soal jalan, Jawa lebih baik. Itu kan menyatakan pengalaman hidup kita sudah beda. Di masa kolonial itu sama, malah ketika dipimpin Indonesia, berbeda.
Jadi, hal penting nasionalisme adalah pengalaman bersama. Orang katakan ketidak adilan, penindasan, eksploitasi sumber daya alam. Itu semua faktor politik. Tapi yang jelas kata kuncinya, kita sudah tidak punya pengalaman bersama.
Ketika pengalaman bersama tak bisa dirawat, maka muncul gerakan pemberontakan, pemisahan diri. Lalu operasi militer terjadi, efek negatifnya terjadi pelanggaran HAM. “Kami di Aceh kok dilanggar HAM-nya, di Jawa kok tidak?” Ini mempertajam pengalaman hidup tak bersama. Ini kerugian menggunakan operasi mi-liter untuk selesaikan pergolakan di daerah.
Jadi menaruh militer di daerah pergolakan kebijakan yang salah?
Saya tidak mau katakan salah atau benar. Yang jelas kebijakan itu makin mempertajam pengalaman hidup tidak bersama lagi.
Bagaimana Anda melihat pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor Timur?
Sama saja, karena pelakunya sama: negara. Negara yang dalam eksekusinya dilakukan oleh militer, khususnya angkatan darat. Pola penculikan sama, penghilangan paksa sama, penyiksaan sama, karena aktornya sama, gak ada yang beda. Jadi gak bisa dikatakan pelanggaran HAM Timor Timur lebih sadis dari Aceh, atau di Papua lebih sadis dari Aceh, gak bisa. Karena pelakunya sama.
Dalam hal ingin memisahkan diri dari NKRI, mana yang lebih kuat?
Papua, Timor Timur dan Aceh beda ya. Landasan politiknya beda. Sejak awal Aceh masuk dalam NKRI. Kalau Papua ada unsur aneksasi. Timor Timur lebih jelas lagi, bahkan penyerbuan. Itu mempengaruhi spirit perlawanannya.
Kenapa Timor Timur bisa lepas?
Karena dukungan internasionalnya cukup kuat. Mereka bagian dari Portugis. Saat itu sentimen aneksasi terkait perang dingin. Komunisme kan? Namun saat Soviet jatuh, situasi globalnya tak ada lagi istilah perang dingin. Orang pun bisa leluasa dukung Timor Timur setelah Soeharto jatuh.
Apakah Papua tak dapat dukungan internasional?
Amerika datang dengan Freeport dan lakukan eksploitasi. Timor Timur eksploitasinya belum terjadi. Papua sudah terjadi. Ini buat repot Papua untuk dapatkan dukungan internasional.
Aceh?
Aceh juga. Pemberontakan terjadi ketika ada Exon Mobile sudah mengeksploitasi. Jadi susah berpisah, karena kepentingan politik dan ekonomi bersatu. Alasan lain kenapa Timor Timur bisa berpisah dari NKRI, selain usainya perang dingin, muncul tokoh seperti Habibie yang rasional saja berpikirnya.
Kenapa sangat susah sekali mengadili penjahat HAM di Indonesia?
Karena sistem politiknya.
Maksudnya?
Pertama, pasca 1955 sebenarnya Indonesia dikuasai militer. Kegagalan Pemilu 1955, puncaknya kudeta 1965, militer sudah di atas. Sampai Soeharto jatuh, masih kuat politik militer. Penguasanya militer, pelaku juga militer, ini yang bikin susah mengadili orang militer.
Lihat di lapangan, pelanggaran HAM bukan terjadi serta merta, namun dilakukan sistematis dan terencana. Makanya sulit sekali diketahui detail-detailnya. Misal para pelaku bisa punya 10 nama.
Kedua, dari sisi korban. Daya tahan mereka terbatas. Umumnya korban pelanggaran HAM masyarakat pedesaan, masyarakat ekonomi menengah ke bawah. ‘Napas’ panjangnya tak sanggup. Karena pelanggaran HAM ditujukan untuk menghancurkan martabat manusia, sehingga mereka tak ada lagi mentalitas perlawanan.
Di masa DOM kita kenal sandi operasi jari merah dengan metode syok terapi. Ini menghancurkan harkat dan martabat serta harga diri sebagai manusia. Contohnya dengan memperkosa.
Lalu di Aceh setelah 1992 dan 1993 dibentuk camp penyikasaan di pos-pos militer. Antar tahanan menyaksikan peristiwa pelanggaran HAM. Korban diperkosa, pertama oleh komandan, lalu anak buah, ketiga diperkosa sesama tahanan dan disaksikan semua. Serdadu seperti orang yang menikmati sebuah show seksual. Bukan sekedar perbudakan seksual tapi sebagai entertaiment bagi serdadu.
Apakah ini perintah dari atas?
Ya, paling tidak komandan membiarkan itu terjadi. Misal kasus di Aceh yang terekam dalam video. Tiap sore orang dibuat seperti adu biri-biri: tahanan disuruh lari dan membenturkan kepalanya. Tahanan dan serdadu lain melihat itu menikmati gitu lho.
Pola pelanggaran HAM kedua baru terjadi setelah 1998, ya kan? Mereka membakar rumah, perkampungan, melakukan penyiksaan, penangkapan orang yang tidak bersalah, dan sebagainya.
Tapi dalam sejarah Indonesia sampai sekarang belum ada pengungkapan pelaku pelanggaran HAM baik yang terjadi pada masyarakat awam maupun kaum aktivis.
Kita perlu belajar pada pejuang HAM masa kekejaman Hitler. Ada suatu komunitas bekerja intensif, tekun sampai mereka memburu pelaku utamanya yang sudah berganti nama, berganti pola hidup di Brazil. Di Indonesia belum ada satu lembaga pun termasuk NGO yang melakukan itu.
Karena ini perlu napas dan biaya panjang. Punya daya survival, daya fight yang tinggi. Pelanggaran HAM di Jakarta saja tak terungkap apalagi di pelosok. Pelanggaran HAM di kelas menengah saja tak terungkap apalagi di kelas bawah. Pelanggaran HAM yang terjadi di perkotaan saja tak terungkap apalagi di pedesaan.
Bagaimana Anda melihat kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah?
Saya rasa konstelasinya ada perbedaan ya, kalau dulu konstelasinya perang dingin, ini kan konstelasi politik. Rezim SBY ini satu pihak buka partisipasi polilitik yang besar, tapi di satu sisi dia tidak lakukan penegakan hukum. Seperti Ahmadiyah. Itu kan jelas kebrutalan golongan agama ke golongan agama lainnya.
Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa satu golongan tertentu tanpa dihukum bisa melakukan kekerasan? Ini kan menunjukkan ketidak beradayaan negara dalam kehidupan, negara tidak bisa mengelola relasi sosial yang baik. Bisa faktor person SBY yang lemah, atau memang situasi politiknya.
Jadi kita kembalikan pembangunan, baik ekonomi, politik dan budaya ke arah pengalaman hidup bersama, dalam konteks nasionalisme. Jangan lihat orang, lihat perilakunya. Lihat perilaku politik yang sering mengklaim dirinya Indonesia itu sering didominasi budaya Jawa, tidak ada penelitian yang menolak ini.
David Brown mengatakan begitu. Terutama masa Orde Baru. Jadi politik Indonesia didominasi budaya Jawa. Jadi ada yang mengatakan pada awalnya nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme anti kolonial, sekarang nasionalisme internal kolonialisasi.
Bagaimana dalam pandangan sosiologi?
Dalam sosiologi intelektual, peran intelektual yang paling penting adalah membangun suatu konstruksi dalam masyarakat. Misal bagaimana intelektual di suatu daerah. Bagaimana perannya untuk menghidupkan kembali bahasa daerah. Itu juga memungkinkan karena ada politik desentralisasi. Namun di sisi lain, masyarakat pengen punya identitas.
Apakah begitu sulit menghukum pelaku pelanggaran HAM?
Banyak aktivis menganggap ini pesimis, tapi kan seharusnya jadi tantangan intelektual. Dan apa yang bisa dilakukan dalam situasi politik seperti ini.[]
sumber: http://bahanamahasiswa.com