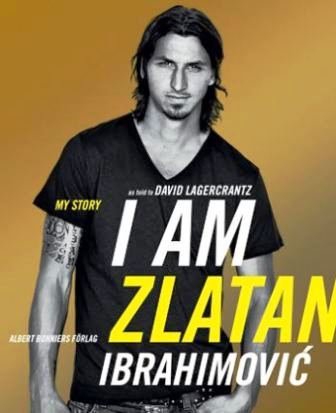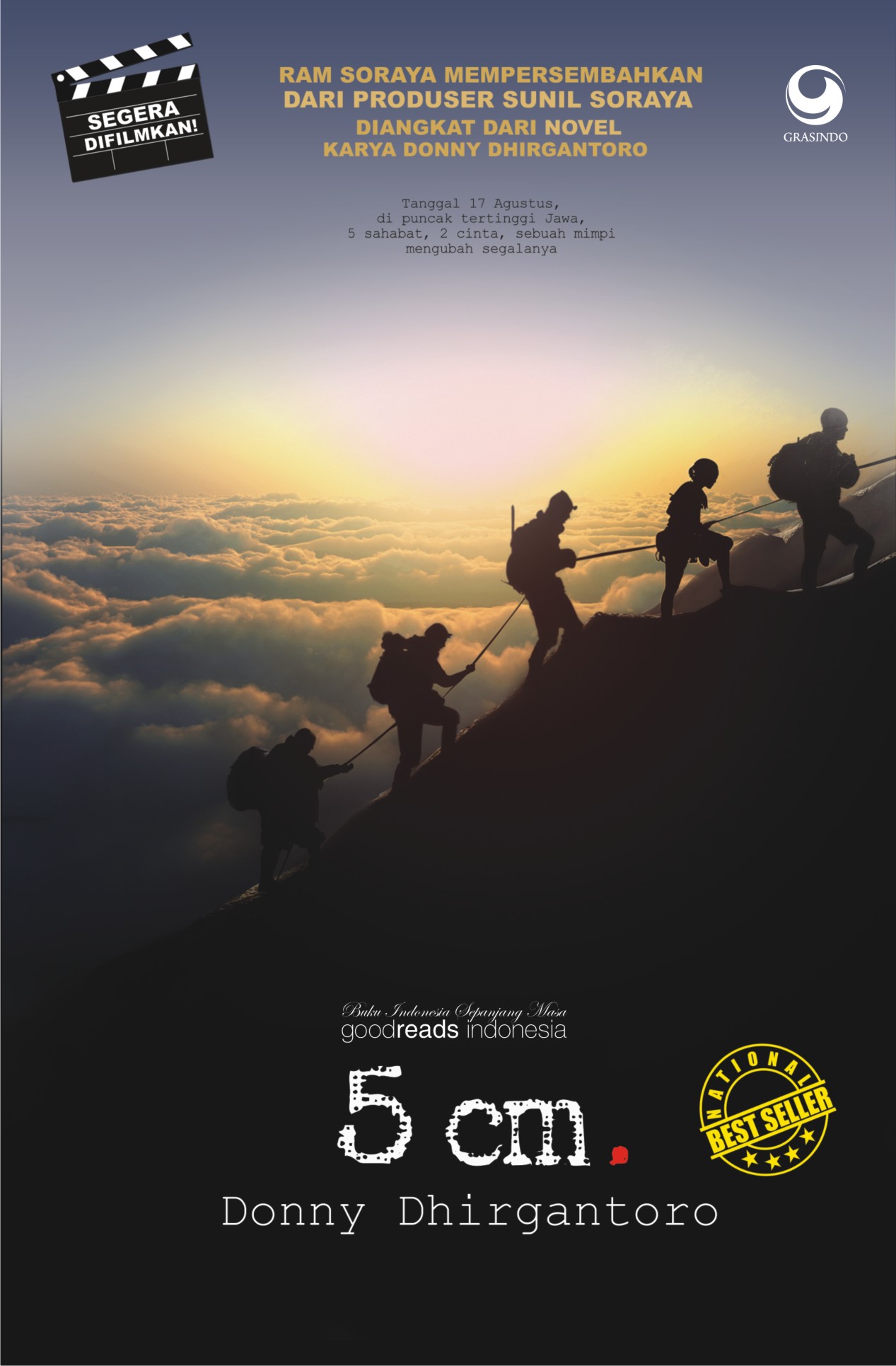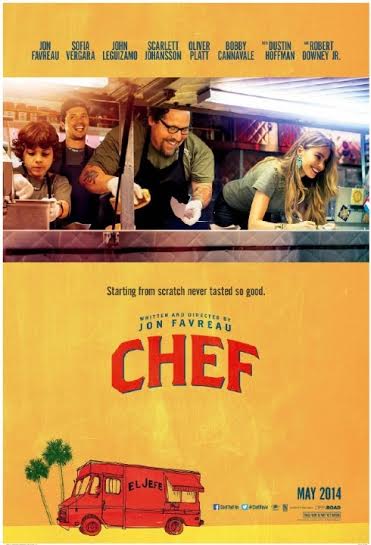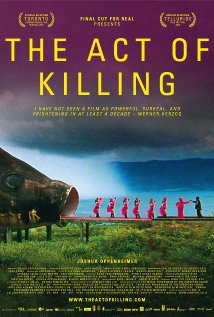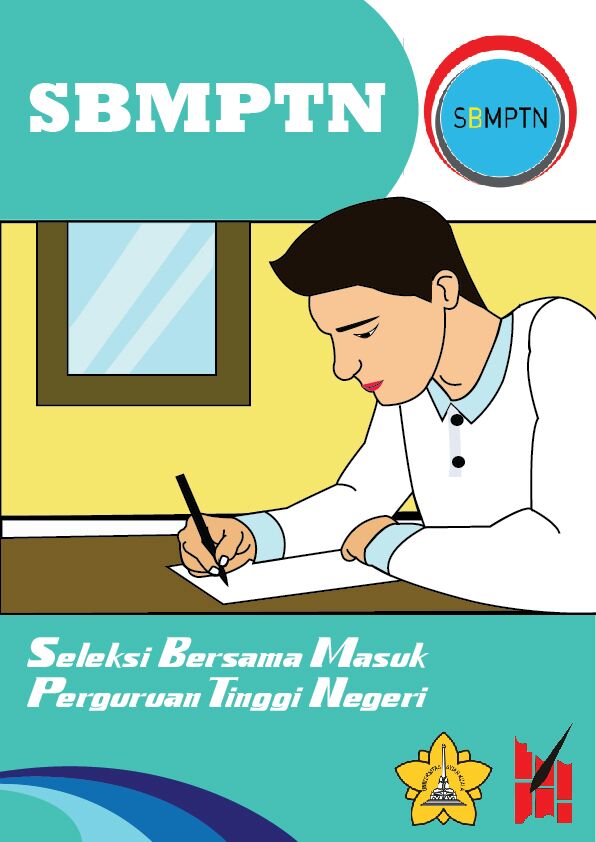Cerpen | DETaK
Aku mendengar jeritan. Wanita atau pria, siapa pun itu.
Aku mendengar suara tubrukan yang keras. Api yang besar terlihat melahap sebuah mobil dan sepeda motor itu. Sepasang suami istri terlihat tergeletak di tengah jalan dengan bersimbah darah. Aku melihat seorang lelaki datang. Ia menghampiri sepasang suami istri yang sudah tak bernyawa itu, berlutut, menangis dan menjerit sejadi-jadinya.
Lelaki ini selalu berjalan di bawah terik matahari dengan kepala tertunduk. Ia melihat orang-orang berjalan tanpa menyapa. Sepatunya terlihat kusam berdebu, terkadang ia membersihkan debu itu dengan tangannya walaupun ia tahu itu tidak ada gunanya. Hidupnya menjadi tak terkendali setelah kematian orang tuanya dua tahun yang lalu. Tentu itu merupakan sebuah cobaan yang berat baginya karena ia adalah anak tunggal—keluarga adalah sahabatnya.
Namun, ia tetap berusaha mengendalikan dirinya untuk terus berada di jalur yang benar dan memastikan dirinya tetap berjalan.
Lukman adalah seorang lelaki pendiam yang duduk di bangku kuliah. Dia dikenal sebagai orang yang biasa-biasa saja—tidak begitu pintar di kelas dan juga tidak terlalu bodoh. Sifat pendiamnya tidaklah membuat dirinya memiliki sedikit teman walaupun terkadang ia merasa sangat kesepian di tengah keramaian.
Hal itulah yang membuat Lukman merasa seperti “berjalan sendirian di dunia ini” pasca musibah tersebut. Kepergian mereka masih ditangisi olehnya. Ia merasa dunia ini begitu kejam terhadap keluarganya. Ia benci dengan semua hal dan melampiaskannya kepada Tuhan dengan kata-kata kasar.
“Sampai kapan kau akan membuatku menderita seperti ini?” Dia meneriaki pantai yang sedang bersantai.
Aku mengerti hal apa yang telah ia lalui di luar sana. Aku tidak akan menyebut namanya kali ini—belum saatnya. Hingga malam tiba, hingga ia lelah mencaci alam dan menutup matanya sejenak. Aku bersyukur karena ia tidak melakukan hal yang lebih bodoh lagi untuk saat ini.
Sang surya telah menampakkan dirinya di ufuk timur. Lukman masih saja betah menghardik dunia. Aku juga tidak heran akan hal itu. Aku hanya dapat berharap semoga ia memulai harinya dengan baik karena aku tahu cacian yang keluar dari mulutnya akan berakibat buruk pada akhirnya.
Lukman kembali dengan sepeda motor sederhana miliknya. Seberkas kilatan cahaya menyorot wajahnya, entah dari mana asalnya. Sebuah kejadian tragis yang menimpa keluarganya terpampang jelas di depan matanya. Tanpa disadari, lelaki ini memacu motornya dengan kecepatan di atas rata-rata sambil menitikkan air mata—aku melihat dengan jernih di kaca spion nya.
Semakin cepat, Lukman semakin tidak sanggup mengontrolnya dan kembali berteriak. Sebuah truk dari arah berlawanan melaju dengan kencang ke arahnya. Aku berusaha keras membuka matanya dari ingatan buruk itu. Dengan terkejut, ia langsung mengelak dari truk itu.
Untuk saat ini motor Lukman berhasil menghindari truk, namun terus mengarah ke sebuah jurang. Lukman sadar—segera ia menginjak pedal rem yang membuatnya berhenti di bibir jurang itu. Aku bersyukur ia kembali fokus dan teriakkan yang kudengar berasal dari dalam truk yang ditujukan kepadanya. Aku melihat matanya memerah penuh dengan api kebencian yang semakin menyala.
“Puaskah kau? Puas? Apalagi setelah ini? Apa?” Lukman kembali meluapkan kebencian pada dunia.
Aku masih belum ingin memanggilnya dari sini. Biarkan ia berjalan, aku tahu ia sedang mencari sesuatu.
….
Lukman menuju ke kampusnya setelah kejadian buruk yang menimpanya. Tetap saja sama, ia masih menyimpan rasa benci itu. Namun, ia tidak perlihatkan di depan teman-temannya. Mungkin ini adalah hal yang tepat untuk menjaga pertemanannya walaupun aku tahu ia membenci mereka. Aku yakin Lukman adalah orang yang beruntung karena sebetulnya teman-temannya peduli terhadapnya. Dia masih belum bisa melihat itu.
Aku bisa melihat dengan jelas ketika teman Lukman menyapanya dengan bahasa yang sangat santun. Lukman—seperti biasa—hanya membalasnya dengan senyuman palsu yang sangat sulit ia lakukan. Semuanya berlalu dengan suasana sunyi sampai pada akhirnya dosen memasuki kelas. Kegiatan pembelajaran berjalan normal dan semuanya berlalu biasa-biasa saja.
Kelas selesai. Lukman menuju ke sebuah taman dan menemani sebuah pohon besar yang sedang beristirahat. Teriknya matahari membuatnya lebih banyak menghabiskan minuman kaleng.
“Aku tidak mengerti, mengapa matahari terlihat hebat dengan cahayanya. Apakah ia tidak memiliki masalah dalam hidupnya? Di usianya yang sudah sangat tua ini, apakah kau yakin dengan semangat yang dipancarkannya itu? Lalu, kenapa aku terduduk di sini? Melihat keindahan alam yang tak pernah ku mengerti apa yang seharusnya ku syukuri.”
Lukman kembali menggerutu dengan matahari. Matanya mulai memberontak dan ia tak sanggup menahan kelopak matanya yang mulai berat. Sejuknya pohon membuat Lukman terlelap pulas di bawahnya. Seorang wanita datang menghampirinya.
“Hai, Lukman!”
Senyuman dan juga suara yang lembut mengiringi gadis itu. Lelaki ini terkejut dengan suara itu dan lekas membuka matanya.
“Oh, hai Dewi,” balasnya dengan senyuman yang dibuat-buat.
“Lelah?” tanya Dewi.
“Begitulah, karena dunia tidak pernah berhenti menguji kita.”
Wanita itu sedikit tertawa mendengar perkataan Lukman.
“Apa yang lucu?” spontan kelopak mata Lukman menjadi ringan—tidak lagi mengantuk.
Dewi hanya menggelengkan kepalanya dan masih memberikan senyuman kepada Lukman.
“Aku tidak melihatmu kemarin, ke mana saja?” gadis ini begitu tertarik untuk menjadi lebih dekat dengan Lukman.
“Mencari ketenangan,” jawab lelaki itu.
“Dan… ketenangan ada di bawah pohon ini?” Dewi melihat sekeliling pohon besar dengan dahi mengerenyit.
“Tidak juga, masih belum kutemukan. Mungkin, tidak akan pernah kutemukan,” cetus Lukman.
“Ada sesuatu yang kau tutupi? Cerita saja,” Dewi melempar senyuman ke arah Lukman, duduk bersila di depannya.
“Aku tidak yakin kau akan mengerti.” Lukman berusaha memundurkan badannya—mustahil badannya bisa memundurkan batang pohon tempatnya bersandar.
“Kenapa?” tanya Dewi semakin penasaran.
Lukman menggelengkan kepalanya dan menghabiskan satu kaleng minuman lagi.
“Kau sedikit berubah sekarang ini,” kini Dewi menatap Lukman dengan serius.
“Aku masih seperti dulu dan tidak berubah sedikit pun,” jawab Lukman semakin cetus.
Dewi mengerti jika lelaki ini mungkin membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Tampaknya basa-basi Dewi tidak mempan bagi Lukman. Dewi langsung pun meninggalkan Lukman bersama pohon besarnya.
“Aku mengerti. Tapi jika kau ingin menceritakannya aku akan mendengarnya,” Dewi menoleh Lukman sejenak, lalu melangkahkan kakinya menjauh dari pohon dengan senyumannya itu.
Aku yakin perubahan yang dialami oleh Lukman juga disadari oleh Dewi. Walaupun begitu, aku masih berdiri di belakangnya sampai ia menemukan apa yang ia cari. Tidak perlu terlalu terburu-buru menyebut namanya sekarang ini. Semua sedang dalam perjalanan dan akan tiba pada waktu yang tepat.
….
Hari mulai gelap. Awan hitam menutupi langit yang sedang memancarkan sinar keindahan di waktu petang—tidak ada senja. Hujan pun mulai turun dengan perlahan. Lukman sedang bersiap-siap menuju ke suatu tempat.
Aku tetap berdiri dan melihat Lukman memakai jaket kulit hitamnya, mengencangkan ikatan sepatunya yang kusam itu, mengambil tas ranselnya yang sedikit berat, lalu berjalan dengan kepala tertunduk. Dia sedang menyalakan sepeda motornya. Matanya masih memperlihatkan benci kepada dunia.
“Apa lagi rencanamu malam ini?” Lukman berteriak—kali ini suaranya pelan.
Lukman mengurungkan niat untuk menancap gas motornya. Pandangannya tertuju pada seorang kakek tua yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Angin yang bertiup kencang membuat kakek itu kesulitan berjalan. Lukman terus menatap kakek itu. Dia terkejut saat melihat kakek itu terjatuh karena kehilangan keseimbangan.
Sejenak aku menatap matanya yang melebar itu seakan tidak percaya apa yang telah terjadi. Aku tahu ia ingin membantu kakek itu. Aku bisa merasakannya. Lukman tidak bisa menggerakkan kakinya untuk melangkah ke sana—sesuatu telah “menancapkan kaki ku ke dalam tanah”. Aku bisa mendengar suara hatinya walaupun tidak begitu jelas.
Lukman berkata sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan sejak kematian kedua orang tuanya.
Lukman terus memperhatikan kakek yang sedang berusaha untuk bangkit itu. Aku sangat yakin dapat mendengar hatinya yang terus berkata “Ayo, kau pasti bisa!” namun ia tidak menyadarinya. Kakek itu berhasil bangkit—berkat teriakan Lukman yang tidak akan pernah terdengar.
Kakek itu melanjutkan perjalanannya, begitu juga dengan Lukman. Perjalanan berlanjut, namun pikiran Lukman tidak jauh berbeda dengan keadaan cuaca saat ini—terombang-ambing oleh angin yang semakin terasa kencang.
“Kenapa kau berjalan sendirian jika kau tahu fisikmu tidak lagi kuat?” Lukman membatin selama perjalanan.
“Kakek itu tidak memaki dunia…”
Walaupun Lukman sudah berkata seperti itu, namun itu masih belum cukup membuatnya sadar. Aku masih harus berada di belakangnya.
….
Tidak mudah untuk terus memastikan agar dirinya terus tetap berada di jalur yang baik. Hari demi hari ia lalui dengan terus mengeluarkan kata-kata cacian. Dia masih belum bisa menerima kepergian kedua orangtuanya. Rasa benci kian menjadi-jadi yang membuatnya terkadang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Lukman mulai memaki teman-temannya yang hendak menyapanya. Dia juga berkata kasar terhadap dosen-dosennya. Tugas-tugas kuliah yang awalnya masih dia kerjakan, sekarang sudah mulai dia abaikan.
Lukman benar-benar telah berada di zona berbahaya. Begitu jauh ia terjatuh di dalam lubang kegelapan. Lelaki ini merasa “seperti berada di dalam sebuah penjara dan terperangkap begitu lama di dalamnya”. Aku melihat kakinya mulai goyah, gemetar dan tidak tahu harus melangkah ke mana—dia hanya duduk bertekuk di sudut dinding penjara, menunggu gilirannya untuk dieksekusi esok. Kedua tangannya juga tidak ingin bergerak untuk lolos dari dalam lubang penjara yang gelap ini.
Aku tidak bisa melihat cahaya sedikit pun. Aku hanya melihat mata Lukman yang sudah tertutup oleh kegelapan. Tidak, aku tidak akan menyerah—aku masih percaya bahwa hatinya masih ada. Hatinya masih bercahaya dan juga masih membisikkan kata-kata.
Hati nuraninya—satu-satunya jalan untuk mengeluarkan Lukman dari mimpi buruk ini. Namun, hal itu tidaklah mudah karena aku mulai berjauhan dengannya.
Aku paham bahwa inilah saatnya. Aku tidak bisa terus berjalan di belakangnya. Kini, aku harus berlari dan memastikan bahwa aku dapat meraih tangannya.
“Hai temanku,” aku mencoba untuk berbicara dengannya.
Lukman tidak dapat mendengarku. Aku harus mengulangi kata-kata itu sampai tiga kali. Lelaki itu menoleh ke belakang dengan wajah penasaran. Aku melihat air mata mengalir dari kedua bola matanya. Aku tahu air mata itu sebuah pertanda jika ia tidak tahu lagi harus berjalan ke mana. Aku kembali menegurnya.
“Hai temanku,” aku menyapanya sekali lagi.
Lukman berlutut sambil menutupi wajahnya. Sungguh, aku mulai merasa kasihan pada anak ini. Aku sudah berlari dan kini aku berada tepat di hadapannya. Aku kembali menyapanya dengan kata yang sama—lagi dan lagi—sambil memegangi pundaknya. Akhirnya, Lukman pun menoleh kepadaku.
“Bangunlah teman dan hapus air matamu. Perjalanan kita belumlah usai,” kataku kepada Lukman.
Aku membantunya berdiri dan mengambil cahaya yang berasal dari hatinya yang sudah terpisah dari tubuhnya. Aku meletakkanya kembali di tempat yang seharusnya.
“Jangan pernah tinggalkan cahaya ini. Dialah satu-satunya penerang yang kita miliki untuk berjalan,” aku mencoba menenangkannya.
Lukman melihatku dengan tatapan penuh harapan. Aku raih tangannya dan ku genggam sekuat mungkin agar tidak terlepas.
….
Malam itu, aku membawanya ke suatu tempat. Cuacanya dingin dan sedikit hujan. Lukman berjalan menuju ke sebuah taman dengan mengenakan jaket kulit hitam untuk melindunginya dari angin malam. Aku juga berpenampilan sama sepertinya. Matanya tertuju pada seorang pria yang duduk di sebuah bangku panjang yang dihiasi oleh sebuah lampu. Lukman melangkahkan kakinya menuju ke sana sedangkan aku terus mengikutinya.
Sepertinya Lukman sudah bisa mendengar apa yang dibisikkan oleh hatinya, walaupun suara itu masih tidak terlalu jelas—hanya aku bisa mendengarnya dengan jelas. Suara itu meminta Lukman untuk mendekati lelaki yang sedang duduk itu. Ya, aku juga memintanya untuk berjalan mendekati lelaki itu. Aku harap ia mau berbicara dengan lelaki itu.
Tampaknya lelaki ini menyadari kehadiran Lukman. Dia menoleh kepada kami dan mengerutkan sedikit keningnya. Pria itu mengenakan jaket berwarna biru gelap dan menutupi kepalanya dengan topi yang ada pada jaketnya—hoodie. Lukman semakin dekat dengan lelaki itu.
“Boleh aku duduk? tanya Lukman.
Sebelum menjawab, lelaki berjaket biru ini melempar senyum pada Lukman. Lukman duduk disamping lelaki itu.
“Tentu saja.” sahut pria itu dengan santun.
“Namaku Vin,” sambung lelaki itu sambil menjulurkan tangannya kepada Lukman.
“Aku Lukman.” Jawabnya sembari menyalami pria itu.
“Senang bertemu denganmu, Lukman. Dari mana asalmu?”
“Kota Haluan. Kau sendiri?
“Bandar Alun.”
Lukman menganggukkan kepalanya dan menyandarkan badannya ke bangku panjang yang ia duduki. Matanya menatap ke depan, sambil mengela napas panjang. Seketika suasana menjadi sunyi tanpa ada yang menyambung percakapan, sebelum akhirnya Lukman melanjutkannya.
“Kau sendiri saja?” tanya Lukman penasaran.
“Apa aku terlihat bersama seseorang sebelum kau duduk di sebelahku?” Jawab Vin dengan sedikit tertawa.
“Bagaimana denganmu?” Lelaki ini balik bertanya.
“Apa aku terlihat bersama seseorang sebelum aku duduk di sebelahmu?” balas Lukman dengan kedua alis sedikit diangkat.
Mereka berdua sedikit tertawa dengan pembahasan yang mereka lakukan ini. Aku melihat ke arah Lukman. Baru kali ini aku melihat ia kembali tersenyum dan tertawa setelah sekian lama keduanya menghilang dari bibirnya. Aku yakin jika itu bukanlah senyuman palsu yang selama ini ia perlihatkan kepada teman-teman kuliahnya. Aku bisa merasakan hatinya mulai sedikit tenang setelah ia tersenyum.
“Kenapa kau sendiri saja? Di mana temanmu? Atau siapa saja seseorang yang menemanimu?” Lukman melanjutkan pembicaraan. Lelaki ini terlihat menundukkan kepalanya sejenak, kemudian ia menoleh kepada Lukman.
“Aku tidak tahu,” jawabnya sambil tersenyum.
“Bagaimana dengan keluargamu? Kau pasti memiliki mereka, bukan?” Lukman penasaran.
Vin menggelengkan kepalanya dan kembali tertunduk.
“Keluargaku sudah tidak ada. Kedua orangtua dan semua saudaraku meninggal dalam sebuah musibah.”
Lukman seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ternyata Vin juga bernasib sama dengannya.
“Aku turut berduka tentang keluargamu, Vin,” kata Lukman. Vin hanya tersenyum.
“Saat itu, gempa bumi melanda kotaku. Getarannya begitu kuat sehingga membuat beberapa bangunan hancur. Aku masih berumur 10 tahun dan aku melihat semuanya. Aku tinggal di rumah bersama ibu dan dua adikku, sedangkan ayahku berada di kantornya. Rumah kami hancur dan menimpa kami semua. Aku terjepit di balik reruntuhan itu.”
“Lalu, aku melihat ibu dan adik-adikku terluka parah. Aku berteriak pada mereka, tetapi mereka tidak membuka mata. Aku mengetahui mereka telah meninggal setelah orang-orang datang dan membawa kami ke rumah sakit.”
Air mata membahasi pipi Vin saat ia menjelaskan semua yang terjadi padanya. Aku juga melihat mata Lukman mulai berkaca-kaca.
“Bagaimana dengan ayahmu, Vin?” tanya Lukman.
“Ayahku berusaha menyelamatkan temannya terjepit reruntuhan dari dalam kantor. Ternyata, ayahku juga tertimpa reruntuhan gedung itu, disamping temannya.” Vin mulai mengusap matanya—walaupun terlihat sia-sia karena ia tidak berhenti mengeluarkan air mata.
“Aku sempat melihat ayahku di rumah sakit yang sama denganku. Ia terbaring lemah. Dan untuk yang terakhir kalinya aku mendengar kata-katanya sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Sungguh kata-kata itu sangat berarti untukku yang hidup sendirian di sini,” lanjut pria itu.
“Aku sungguh turut berduka tentang keluargamu,” kata Lukman lagi. Lukman menghela nafas panjang. Vin menganggukkan kepalanya. Kali ini, Vin berhasil menghapus air matanya dengan jaketnya.
“Kau tahu, aku bersyukur karena Tuhan masih menyayangiku. Walaupun Tuhan sudah memanggil keluargaku, Aku yakin Tuhan masih menyebut namaku untuk terus berjuang di sini. Meskipun, aku harus berjalan dengan kedua tongkat ini.” Vin memperlihatkan kedua tongkat tersebut—sebagai pengganti kakinya yang sedang beristirahat karena tertimpa reruntuhan saat gempa.
Lukman semakin sedih mendengarnya.
“Kau tidak marah pada Tuhan? Aku kira Tuhan sudah berlaku tidak adil padamu.” Tanya Lukman—kali ini matanya sedikit memerah.
“Kenapa aku harus marah pada Tuhan? Berkat kejadian itu, aku semakin paham bahwa Tuhan begitu menyayangi diriku. Dengan begitu, aku semakin menyayangi diriku sendiri,” Vin tersenyum tipis.
“Walaupun aku sendirian di sini, aku sangat bersyukur karena Tuhan memberiku hati yang kuat. Sekarang, aku sangat bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan aku dengan dirimu. Tidak banyak orang yang menyapaku, mungkin karena kondisiku seperti ini. Namun, kau melakukannya,” Vin kembali tersenyum kepada Lukman. Sungguh, ia begitu ikhlas dalam menjalani hidupnya.
Lukman seolah tidak percaya ketika mengetahui bahwa masih ada orang yang lebih menderita dari dirinya. Selama ini, ia selalu mengutuk dunia dan Tuhan karena ia menganggap Tuhan tidak adil pada dirinya. Vin membuat Lukman menyadari sesuatu.
“Lalu bagaimana denganmu? Kau terlihat sedikit misterius.” Vin balik bertanya.
“Mungkin kau tidak akan percaya jika aku bernasib sama sepertimu. Hanya saja Tuhan lebih ingin mendengar kata-katamu daripada diriku. Mungkin juga Tuhan membenciku.”
Walaupun Lukman masih berkata demikian, aku tahu jika cahaya di hatinya itu kini mulai menyebar ke tubuhnya.
“Tidak. Jika Tuhan sudah tidak lagi mendengarmu, kau tidak mungkin merasa kasihan tentang keluargaku. Kau masih memiliki hati yang baik, Lukman. Kau masih bisa merasakan sesuatu yang membuat hatimu bergetar. Percayalah, kau hanya belum menyadarinya.”
Sungguh, perkataan Vin membuat Lukman kembali membuka matanya. Tidak sia-sia aku membawanya kepada pria ini. Dia sangat membantuku untuk menyadari Lukman yang terperangkap di dalam penjaranya sendiri—seolah membagikan cahaya hatinya kepada Lukman.
“Lihatlah di sisimu. Bisakah kau membedakan warna-warna yang kau lihat itu? Tutuplah matamu dan rasakan udaranya. Hiruplah udara itu perlahan dan rasakan ketenangannya. Jika kau menyadarinya, itu pertanda bahwa Tuhan masih mendengarmu. Tuhan tidak pernah berlaku tidak adil pada orang-orang, termasuk pada kita,” jawab Vin dengan senyum yang semakin lebar.
Lukman tertunduk dan menangis. Kali ini dia mengerti dan tidak seharusnya dia memaki Tuhan dan alam. Dia sungguh sangat menyesal telah melakukannya. Cahaya itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Matanya benar-benar terbuka dan ia bisa melihat banyak hal yang tidak pernah ia lihat sejak kedua orangtuanya meninggal.
….
Dari dalam lubang itu, aku melihat sebuah tangga. Aku tidak tahu entah dari mana datangnya tangga ini. Aku menjulurkan tanganku kepada Lukman.
“Ayo teman, saatnya kita keluar dari sini! Kita akan memulai perjalanan hebat dan langkah kita akan di mulai saat kita berada di atas lubang ini.”
Lukman pun meraih tanganku dan menggenggamnya sekuat mungkin.
“Jangan lepaskan genggamannya.” kata Lukman kepadaku. Perkataannya sungguh membuatku terharu. Aku juga menangis saat itu.
Aku berkata, “Tidak akan.”
Aku menggendong Lukman dan terus mendaki dari mimpi buruknya. Ketika kami tiba di atas, sungguh pemandangan di luar sangat mengagumkan. Aku sangat berterima kasih pada Vin yang telah membantu Lukman keluar dari penjaranya.
“Berteman?” Vin menjulurkan tangannya kepada Lukman.
Lukman menoleh ke arah Vin dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk tubuh Vin dengan amat erat sambil menangis terisak-isak. Vin juga membalas pelukan temannya itu dengan hangat.
Kini, aku tidak perlu lagi menyimpan hal-hal buruk. Kejadian yang telah berlalu hanya akan menjadi kenangan saja. Pada akhirnya, aku akan memilih karena aku tahu semua butuh pilihan. Aku sangat bersyukur dapat melaluinya dengan berbagai macam pelajaran. Hingga pada akhirnya, Tuhan mempertemukan Lukman dengan seorang teman.
Aku telah mengenal Vin dengan baik sekarang. Dia lebih dari seorang sahabat karena kini ia adalah saudaraku. Ia telah membantu seorang lelaki yang terperangkap dalam kubangan depresi, jeruji besi yang memenjarakan jiwa dan pikirannya.
Sekarang Lukman benar-benar telah merdeka, sementara aku sudah kembali ke tempat di mana seharusnya aku berada. Mereka memanggilku Lukman, bahkan Vin juga memanggil namaku seperti itu.
Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Akulah si pemilik nama itu, Lukman.[]
Penulis bernama Reza Fahlevi. Ia merupakan mahasiswa jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala.
Editor: Mohammad Adzannie Bessania