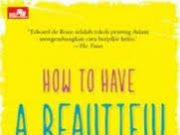Cerbung | DETaK
Apa itu pernah terjadi sebelumnya? Ya dan tidak.
Ya, kalau pertanyaannya hanya sebatas apa aku pernah mencegah penglihatanku terjadi.
Tidak, kalau pertanyaannya apa penglihatanku benar-benar terjadi karena aku berusaha menceganya.
|
IKLAN
loading...
|
Masa depan adalah sesuatu yang pasti, namun melihatnya dari masa lalu merupakan hal yang lain lagi. Apa yang bisa kita dapatkan adalah prediksi, dan tidak akan lebih dari itu. Bahkan dengan kemampuanku.
Aku pernah mencoba mencegah masa depan terjadi, dan efeknya berubah dari apa yang kulihat. Hanya satu kali, Aku tidak mau terlalu sering bermain-main dengan masa depan.
Suatu kali aku berjalan sepulang sekolah sehabis melihat-lihat jalanan seperti biasa. Aku melalui satu trotoar di pusat kota, masih mengenakan seragam, dan minum sekaleng soda dingin. Cuaca siang itu sangat panas. Aku bisa merasakan matahari membakar sampai ke kulit kepalaku. Aspal hampir-hampir meleleh bersama ban-ban mobil yang mentereng di tepi jalan.
Aku berhenti karena tertarik ke satu pemandangan nan sibuk yang terasa sangat janggal di tengah hari yang gerah itu, di mana kebanyakan orang waras akan leyeh-leyeh di depan kipas angin sambil nonton siaran ulang pertandingan football. Di seberang jalan, aku memperhatikan toko bunga yang sedang direnovasi. Toko dua tingkat itu tampak seperti toko-toko lainnya di deretan yang sama: ruko satu pintu sederhana yang dicat hijau. Aku sering lewat di jalan itu, tapi tidak pernah melihatnya lebih ramai dari ini sebelumnya.
Beberapa orang dengan seragam pekerja overall bewarna biru lalu lalang sambil membawa berbagai perkakas, keluar-masuk melalui pintu yang diganjal dengan sebuah pot batu kosong.
Sebenarnya toko itu belum berubah banyak, kecuali jendela panjangnya tidak lagi ada di sana. Barangkali baru akan diganti. Bunga-bunga dalam pot tembikar masih bergelantung di beberapa sudut kanopi. Tali-tali jeraminya dianyam seperti sabuk makrame. Bunga-bunga yang lebih kecil dipajang dalam pot mini di dalam dan luar ruangan, sedang dipindahkan dari rak-rak kayunya. Beberapa pot raksasa berisi tanaman yang hanya punya daun lebar di singkirkan ke satu sudut, sedangkan potongan-potongan bunga segar berbagai jenis dan warna disusun di pojok lain dalam bungkusan kertas besar.
Sang pramuniaga, wanita muda berusia dua puluhan tahun sedang bertengger di tangga lipat, berusaha menurunkaan tanaman gantung yang mengganggu pekerjaan para tukang.
Dari sebuah balik truk pengangkut yang sedang parkir di depan toko, dua orang pria keluar membawa selembar kaca besar, hampir sebesar meja pingpong.
Selama sesaat kukira tidak akan ada yang menarik daripada menonton renovasi sebuah toko bunga hidup. Tepat sebelum aku menoleh dan kembali berjalan, mendadak serangan nyeri di balik mataku muncul. Ledakan sinar lagi, seperti mataku disorot lampu panggung.
Dari pandanganku, kulihat wanita itu memegang tali serabut dari pot gantung di kedua tangannya. Dia praktis tidak bisa menjaga keseimbangannya tanpa mencengkeram ibu tangga.
Belum sampai kakinya menyentuh anak tangga pertama dari puncak saat mencoba turun, kakinya kehilangan pijakan. Kaki tangga mulai bergoyang, kentara akan menjatuhkan wanita itu. Bagian terburuknya, aku bisa melihat dia jatuh ke atas lembar kaca yang sedang dibawa.
Setengah detik berikutnya, batang lehernya mendarat tepat di sisi tipis kaca dengan bunyi krak yang mengilukan. Kepalanya miring ke arah yang tidak wajar, matanya berputar hingga tinggal putihnya, dan seakan belum cukup buruk, bagian atas tangga miring dan menghantam tengkuknya, membenamkan kaca hingga ke daging lehernya. Kini kepalanya benar-benar miring dengan sudut yang tidak wajar. Darah kental terciprat dan mengalir, bersamaan dengan kekagetan para pekerja.
Mereka menjatuhkan lembaran kaca itu hingga pecah berkeping-keping. Beling dan noda merah menyebar ke sepenjuru emperan toko. Tubuh wanita itu mengejang. Dari mulutnya keluar erangan yang bersambut dengan muntahan darah kehitaman. Tiga detik berselang pandangan itu hilang.
Belum pulih dari pitam, aku berlari menyeberang jalan secepat yang kubisa. Bahkan aku tidak sempat mendapat penglihatan bahwa aku nyaris terserempet taksi, barangkali karena peristiwanya tidak lebih krusial daripada hidup-matinya wanita itu. Hanya tiga detik tersisa, dan aku bisa melihat semua orang sudah berada pada posisinya masing-masing, persis seperti dalam visiku. Wanita itu menyadari kehadiranku, menoleh, dan tersenyum padaku, mungkin mengira barangkali aku adalah pelanggan. Sejenak ketika perhatiannya teralihkan itulah pijakannya goyah.
Tepat pada waktunya, aku berhasil meraih dan memegangi kaki tangga, menahannya. Nahas bagiku, tarikan itu terlalu kuat sampai tangga itu condong ke arah sebaliknya.
Membiarkan gravitasi mengambil alih, tangga itu seolah hendak memberiku kecupan terima kasih. Wanita itu terjatuh bersama tangga dan menimpaku di antara trotoar. Tubuhku terhimpit dan rasanya punggungku remuk. Dadaku menahan beban dari salah satu anak tangga. Aku terbatuk sambil mengerang kesakitan. Tidak pernah terbayang dalam visi lima detikku yang lain bahwa aku akan jadi roti lapis bersama jalur pejalan kaki dan tangga lipat.
Pot gantung yang dipegang wanita itu kini jadi potongan-potongan kecil tembikar. Tanah dan tanaman di dalamnya berserakan di sebelahku. Bahkan kurasa aku dapat asupan pupuk kandang. Harus kuakui rasanya tidak enak.
Wanita itu jatuh dengan separuh tubuh masih tersangkut pada tangga. Dia berguling jatuh ke trotoar dan berdiri sempoyongan di sebelah kepalaku, nyaris menginjak tanganku. Aku masih berusaha menyingkirkan himpitan tangga itu saat kuliat dua orang tukang mengangkatnya.
Setelah bebas, aku mencoba sebisa mungkin untuk bangkit. Pergelangan tanganku terkilir. Perut dan dadaku memar, dan kepalaku benjol. Wanita itu sendiri mendapat luka terkelupas di telapak tangannya. Ah, hari yang indah untuk dapat luka baru.
Singkatnya, kami saling meminta maaf. Meskipun wanita itu tidak menanyakan alasanku bergegas menyeberang jalan dan memegangi kaki tangga untuknya, aku tetap mengarang cerita tentang tangganya yang kelihatan tidak seimbang sejak awal. Aku tidak yakin kalau dia akan percaya, namun dia tidak mempermasalahkannya.
Untungnya dia tidak meminta ganti rugi dua pot yang pecah itu. Wanita itu menganggap itu bukan sepenuhnya salahku. Padahal belakangan ini aku tahu bahwa harga sepasang tanaman hias yang hancur itu bisa memberiku satu unit ponsel keluaran terbaru.
Beruntung apa yang kulihat sebelumnya tidak terjadi. Dan lebih beruntungnya lagi, kejadian yang menyusul atas tindakanku jauh lebih baik.
Aku mengingat kejadian itu saat menelusuri jalanan yang mulai dipenuhi orang-orang yang berhenti untuk menyaksikan kecelakaan. Ingatan itu seolah jadi tameng agar aku tidak terguncang. Barangkali aku berusaha meyakinkan diriku bahwa kali ini kejadiannya sama.
Aku akan menyelamatkan siapa pun pengendara motor itu, kan? Atau tidak?
Kecelakan itu tidak ada hubungannya dengan bus yang berhenti mendadak, kan? Atau memang ada?
Semakin dekat dengan titik pusat tampat kejadiaan, sepatuku mulai menginjak bagian-bagian motor yang tidak lagi berbentuk. Ada beling, pecahan logam dan potongan kecil plastik badan kendaraan. Lalu ada darah. Banyak darah. Titik-titik yang lebih gelap di aspal, berkilat oleh cahaya matahari.
Aku semakin tidak bisa mengontrol napasku. Bumi seolah membuka lubang besar tepat di bawah kakiku. Aku berhenti melangkah, tidak berani melihat lebih jauh apa yang sudah kusebabkan.
Kecelakaan itu terjadi tepat di depan mataku. Dua kali. Dan aku adalah penyebabnya. Nyawa seseorang sedang dipertaruhkan karena pilihanku.
Tanpa sadar aku mulai menangis. Air mata jatuh namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Napasku tercekat. Tenggorokkanku seolah disayat dari dalam. Semua ini, bakat—bukan—kutukan ini, terlalu berat untuk kutanggung sendiri.
Aku jatuh berlutut di tengah jalan. Orang-orang melewatiku tanpa menoleh dua kali. Mereka hanya ingin melihat apa yang menghalangi mereka meneruskan perjalanan di pagi yang lembab ini.
Aku mulai terbatuk, tersedak dengan ludahku sendiri. Sementara air mata terus mengalir jatuh, menetes ke bekas darah, perutku bergejolak. Dua detik berikutnya, sarapanku keluar dalam bentuk bubur asam lambung yang menjijikkan. Aku muntah-muntah di tengah orang banyak Aromanya membuatku tambah mual, namun yang keluar selanjutnya hanyalah cairan bening. Tenggorokanku sudaah benar-benar perih sekarang..
Memalukan, tapi perasaan itu menghilang secepat datangnya. Rasa bersalahku membesar kembali. Beberapa menyadarinya dan memberikanku simpati kecil di tengah kekagetan mereka. Wanita dengan dua anak yang juga merupakan penumpang bus yang sama denganku membantuku menepi ke belakang bus, memberiku sebotol air sementara kedua anaknya menatap keramaian dengan wajah penuh tanya.
“Kamu tidak apa-apa?”
Tubuhku pasti gemetar sangat hebat sampai-sampai dia mengelus bahu dan tengkukku pelan-pelan. Aku mencoba meliriknya, tapi yang kulihat tidak lebih dari rambutku yang meneteskan keringat dingin.
“Tidak ada yang perlu ditakutkan,” katanya lagi. “Polisi dan ambulan akan tiba sebentar lagi. Korban akan selamat.”
“Ma, ada apa?” tanya salah satu anaknya.
Aku terlambat sadar bahwa kedua anak wanita ini kembar, mungkin karena mereka memakai pakaian yang berbeda dan masing-masing memakai masker. Keduanya memandangku dengan tatapan takut.
“Tidak ada apa-apa, Nak,” jawab ibu itu dengan lembut. “Sebentar, ya. Mama telepon ibu guru kalian bilang kita terlambat ke sekolah hari ini.”
Kedua anak itu mengangguk, kembali menatap jalanan yang ramai dengan gelisah. Sang ibu menghubungi seseorang yang pasti guru sekolah anaknya, menjelaskan situasi yang menghalangi perjalanan mereka.
“Jalan ditutup,” terang wanita itu padaku setelah menelepon. “Dua ban truknya pecah, dan posisinya miring di tengah badan jalan. Sampai mobil dereknya tiba, kita masih terjebak disini.”
Aku tidak menanggapi penjelasannya. Seluruh tubuhku masih gemetar dan pikiranku masih melayang ke kejadian itu, seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang.
“Firasat kamu kuat,” akhirnya dia berkata.
Aku menoleh padanya, cemas atas apa yang mungkin dia ketahui dari hanya memperhatikan gerak-gerikku. Mungkin pandanganku terlalu menakutkan sehingga sejenak dia terlihat menyesal telah menolongku.
“Kalau kamu tidak minta supir berhenti, separuh bus ini bisa remuk karena tabrakan beruntun. Bagian depan truk dan bus cuma terpisah dua meter di posisinya sekarang.”
Aku mengangkat wajahku dan menatapnya dengan mata terbelalak.
Apa maksudnya…aku…?
“Saya tidak tahu bagaimana kamu tahu apa yang harus dilakukan, atau bagaiamana naluri kamu bisa sekuat itu, tapi saya, anak-anak saya, dan penumpang bus lain, selamat karena kamu,” jelasnya.
Aku ingin memercayai wanita ini, namun aku tidak yakin unutk apa. Apa karena simpati yang ditunjukkannya padaku? Apa karena itulah hal yang ingin kupercayai—bahwa aku mungkin menyelamatkan nyawa orang dari akhir yang mengenaskan? Atau aku semata-mata terlalu pengecut dengan apa yang lebih kupercayai saat itu—bahwa aku mungkin telah membunuh seseorang?
Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Selama sejenak kami duduk di trotoar dalam hening, di tengah hiruk pikuk orang yang masih menonton dan menunggu kembalinya lalu lintas. Dia kemudian mengajakku kembali menunggu di bus, menggendong salah satu anaknya dan memegangi tangan yang satunya.
Dengan mata perih dan kepala sakit aku mengikutinya masuk ke dalam bus. Menunggu bersama penumpang lain yang dengan jengah mengeluh tentang keperluan mereka yang berujung pada keterlambatan dan pembatalan. Aku kembali ke tempat dudukku di belakang, sementara wanita itu mengambil tempat satu baris di depanku, jauh dari tempatnya semula.
Aku masih memikirkan rentetan kecelakaan itu, kemungkinan bahwa akulah yang menyebabkannya, dan kemungkinan bahwa aku jugalah yang menyelamatkan bus ini. Semua bercampur dalam kepalaku seperti air dan minyak. Seperti potongan teka-teki dengan bentuk dan dari gambar yang berbeda. Tidak berhubungan dan tidak dapat disatukan.
Tidak lama kemudian tiga orang polisi muncul dari balik kerumunan. Mereka memerintahkan semua orang menepi dari korban, mengarahkan ambulan, dan mengamankan pengemudi truk.
Setengah jam kemudian, mobil derek datang dan membawa truk pengangkut. Jalanan dibersihkan dan kendaran kembali meraung-raung, menyusul keterlambatan.
Polisi praktis menahan seluruh penumpang bus untuk dimintai keterangan. Tidak ada yang memuaskan. Mereka mengatakan hal yang mereka lihat. Aku tidak bisa mengenyahkan firasat bahwa mereka sengaja menutup mulut mengenaiku karena tidak yakin apa memang tindakanku berhubungan dengan kecelakan itu. Atau mereka memang sama sekali tidak menganggap tindakankulah yang menyebabkannya? Namun untuk sementara pria-pria berseragam itu meminta kontak kami semua kalau-kalau ada kejanggalan yang ditemukan.
Bus kembali berjalan namun dunia seolah berhenti di sekelilingku. Dua perhentian berikutnya, ibu dengan dan anaknya turun dari bus. Seharusnya aku turun di halte berikutnya di dekat sekolah, namun aku sudah bertekad bolos hari ini. Lagipula aku sudah terlambat.
Aku harus ke rumah sakit. Aku harus memastikan keadaan pria itu—si korban—dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus tahu apa peranku dalam kecelakaan itu: pembawa petaka atau penyelamat.
Bersambung ke chapter 4
Penulis bernama Teuku Muhammad Ridha, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil USK angkatan 2019, Ia juga merupakan salah satu redaktur UKM Pers DETaK Unsyiah.