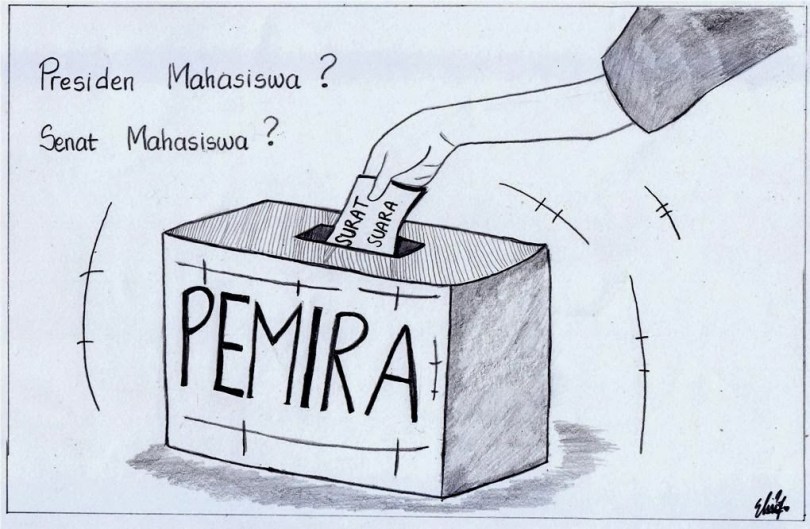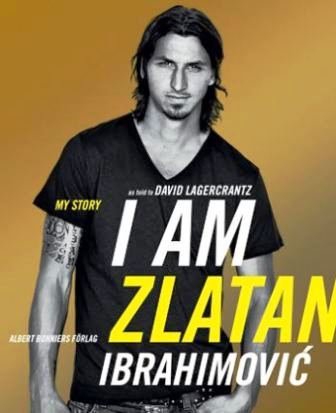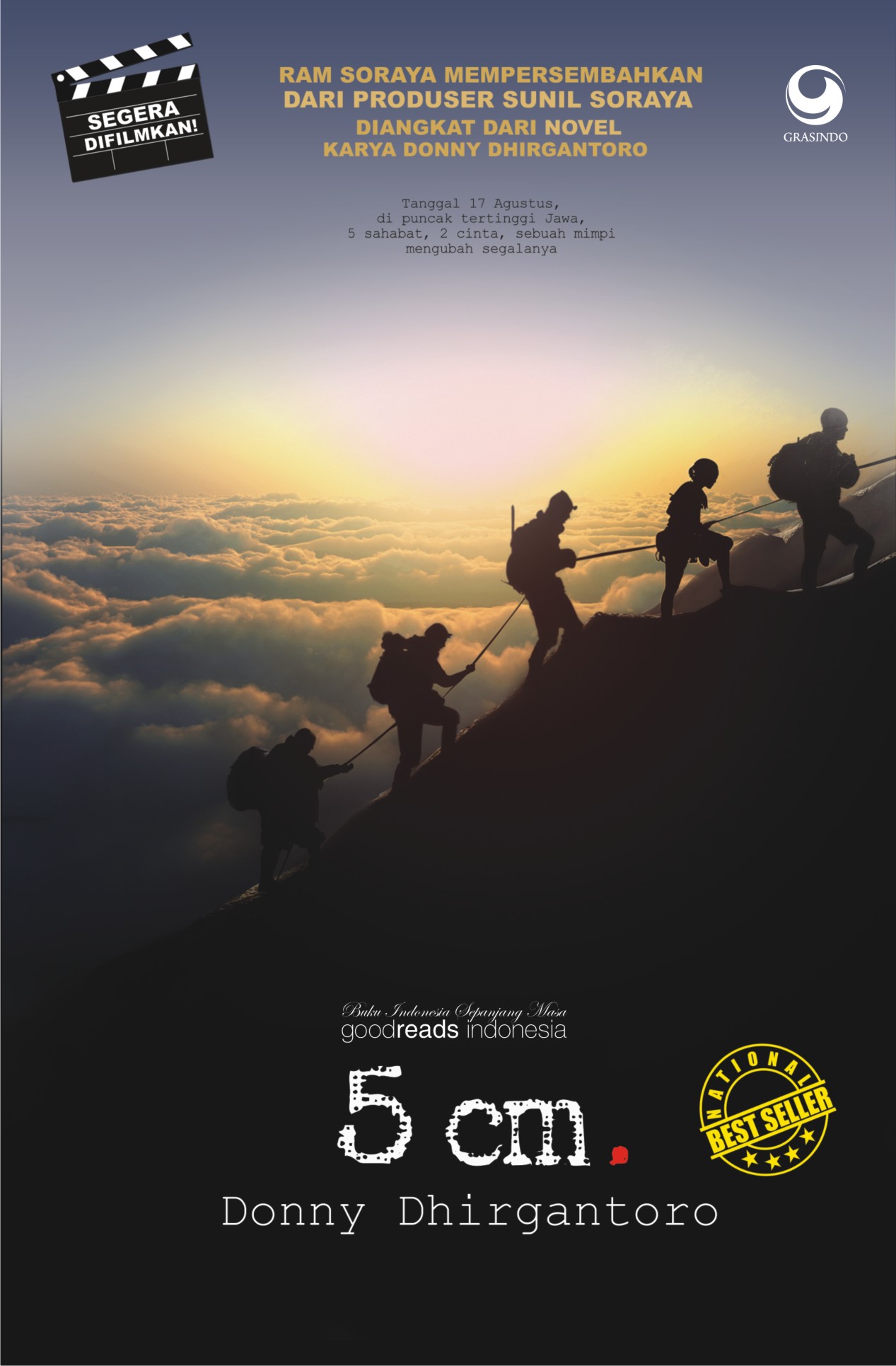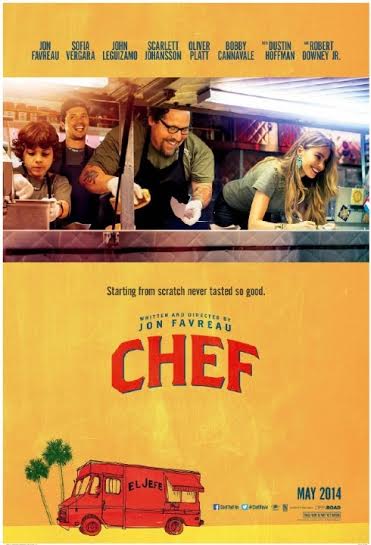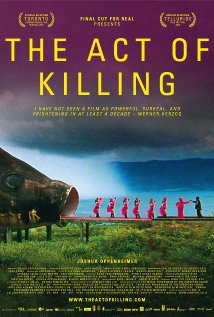Cerpen | DETaK
Oleh : Radhia Humaira
An der schÖnen, blauen Donau
(Di tepi sungai Donau yang indah dan biru)
judul sebuah Waltz oleh komponis Austria, Johan Strauss.
Kata itu tertulis besar dalam font Georgia pada selembar kertas terpajang di dinding kamar. Di sampingnya, Benua Eropa terpapar jelas serta gambar bangunan tua Jerman, mulai dari katedral Ulmer Munster, The Rathaus (City Hall), Museum of Bread Culture hingga potret Kota Ulm, kota tua nan cantik di sisi Danube, tepatnya di Barat Daya Jerman.
Kota kelahiran fisikawan Albert Einstein itulah pertama kali membangun mimpinya. Disusul Danube, sungai terpanjang ke dua di Eropa setelah sungai Volga ke barisan mimpi di bawahnya. Ada “suatu saat” yang wajib Ia jalani, sehingga Ulm dan Danube jadi pelayaran terjauh, Tetapi untuk sementara waktu, masih membingkai tetap, tepat di matanya.
“Suatu saat kita berenang di sana” gurauku padanya seraya menunjuk gambar Danube
“Apa Danube tidak terlalu dalam untuk Kita berenang?” pertanyaan lugu putra 12 tahun hadirkan lekuk bahagia di wajahku
“Tidak sedalam tatapan Kita sekarang untuk Danube, nak. Kita akan ke sana!”
Tugas seorang Ayah adalah meyakini putranya menggapai impian. Sebab itu mengapa aku sangat optimis tentang suatu saat kita yang akan dijalani bersama. Minggu malam, aku menemaninya menyusun rencana beberapa tahun ke depan. Gurunya memberikan tugas menulis 100 target untuk 12 tahun mendatang di lembaran HVS agar dibacakan esok hari. Malam itu, Aku memberikan gambaran mimpi-mimpi besar kepadanya. Aku bercerita sedikit banyak tentang para ilmuan dan tempat bersejarah yang indah sepengetahuanku. Dari sekian yang tersebutkan, Ia sangat tertarik pada Einstein. Sehingga Ia menulis kota Ulm dan Danube sebagai destinasi pertama yang akan dituju.
Tersimpulkan sudah tujuanku…
Membangun Danube di benaknya.
Sejenak teringat pada beberapa tahun lalu ketika bertemu dengannya adalah hal sederhana yang merumit. Sederhananya, disebabkan aku sebagai seorang Ayah mempunyai hak bertemu, kerumitan adalah izin dari Ibunya yang tersimpul mustahil. Tapi sebatas itulah kuasa manusia menghalangiku bertemu anakku, lebih besar kuasa Allah untuk mempertemukan Kami.
Lebih jauh dari itu, teringat lagi ketika pertama kali aku merasa kemenangan. Kala itu, usianya 9 tahun, Dia membiasakan diri tinggal di rumahku, karena Ibunya menyambung pendidikan ke luar Negeri bersama suami barunya. Zaid-Nama yang ku beri-, memilih tinggal bersamaku karena tak ingin mengganti lingkungan sekolahnya. Mereka berdua juga setuju Zaid bersamaku. Jika boleh bercerita lebih, aku ingin katakan bahwa ketika mereka berangkat, masih juga tak memberitahu tentang nama anakku, sebab itu aku memanggil dengan sebutan Zaid. Setelah keesokan harinya, saat aku lebih pintar mendekatkan diri dengan Zaid dan bertanya kepada guru di Sekolah tentang nama anakku, baru ku ketahui bahwa namanya persis seperti namaku, Bakhtiar.
Entah apa maksud Ibunya dulu memberikan nama seperti itu.
Tapi aku terlanjur betah memanggilnya Zaid, ada yang bernilai di sana.
Zaidku kini telah berusia 17 tahun setengah. Baru saja Ia wisuda dari Sekolah Menengah Atas sebagai lulusan terbaik. Satu lagi urutan mimpi 100 target-yang dibuatnya dulu- ia lingkari. Tandanya, target telah tercapai. Kebetulan, target tersebut tepat tertulis di urutan ke-17, angka 17. Sebab itu, betapa menariknya mengenang usia 17 tahun Zaid.
Beberapa minggu setelah kelulusan, pendaftaran tingkat Universitas dibuka. Sebelumnya, Zaid bersama kawan-kawan telah didaftarkan di jalur undangan atau SNMPTN oleh gurunya. Syukur, Zaid dan beberapa temannya lulus di Universitas ternama di Indonesia. Zaid, ada saja caramu memahat prestasi.
Ku rasa, tidak perlu ku luahkan bagaimana kegembiraanku dengan hasil yang selalu dibawa pulang Zaid. Aku hanya ingin menjadi Ayah bijak untuknya. Sebab itu, aku tak pernah membanggakan Zaid di depan Ia sendiri, cukup Ia menjadi ceritaku pada neneknya juga beberapa teman dekat yang ku percaya tak akan menceritakan cerita pujian ini pada Zaid. Untuk mendukungnya, cukup menghadiahi senyuman setiap ia menyampaikan prestasinya. Sejauh ini, semua masih baik-baik saja, walau hanya respon senyuman, tetap saja Zaid tak mengeluh. Ia Zaidku yang enggan mendung.
Zaid mendekat ke mading di kamar -tempat Danube dan mimpi-mimpinya bersemi-,
“di sini, tak ada target untuk berkuliah di Universitas ternama di Indonesia, Yah”. Ujarnya
Cepat aku menghampiri mading dan menyisir target itu dengan mataku dari angka satu hingga tiga ratus. Zaid menambahkannya sendiri dua ratus target setelah beberapa tahun hanya bertahan dengan seratus target. Benar, Zaid tak pernah menuliskan target tentang prestasi hari ini.
“itu artinya, kamu harus menulisnya di angka tiga ratus satu, Nak” saranku
“gak bisa dong Yah. Gak ada esensi “targetnya”. Yang namanya target, lahir sebelum usaha. Menurut aku, setiap yang aku tulis adalah hal yang ku ingini. Kesimpulannya, aku tidak ingin ke sana. Aku di Universitas di sini aja”
Kesimpulan pertama yang dibuat tanpa persetujuanku. Ia benar-benar hanya memilih kualitas di sini. Katanya, Dia lebih baik tinggal bersamaku. Ada sesuatu yang dikhawatirkan…
Berulang kali ku eja bahwa untuk bisa mencapai target pertamanya (kota tua Ulm dan Danube) berarti Ia harus menjadi pintar agar dipercaya orang, terkenal, mendapat pendidikan bagus dan beasiswa. Pergi dengan biaya sendiri, Ulm dan Danube adalah kemustahilan yang nyata.
Hari ini, Danube yang menjadi “suatu saat kami” perlahan terkikis karena “suatu saat” yang dikhawatirkan Zaid. Ia menyinggung tentang kematian.
“Apa yang memberatkanmu?”
Pertanyaanku itu lalu menjadi jalan kami agar saling terbuka tentang suatu saat yang kita khawatirkan. Kita saling menceritakan tentang siapa yang akan pergi duluan. Aku atau Zaid? Dalam pertanyaan itu, kami sama-sama dicekik geming. Tak mendapati jawaban meski hanya sebuah jawab praduga, hampir terbenam dengan debat usia, sebelum kembali tawakkal. Teka-teki itu takkan mampu dipecahkan.
“Baiklah Zaid, anggaplah ini pertanyaan kecilku, mengapa kau ingin tetap dengan ku? Tanpa alasan siapa diantara kita yang mati duluan”.
Jawaban Zaid sangat padat, ada hal yang bisa Ku simpulkan.
Selayak Nil dengan Danube, Ia tak ingin kita punya spasi selayak itu. Bagaimanapun, suatu saatku adalah bagian dari suatu saatnya. Aku atau dia pasti akan membutuhkan satu sama lain.
Aku merasa bersalah atas harapan yang terlalu banyak ku nyalakan untuknya. Bahkan, perlahan Ia lebih besar dari Zaidku sendiri. Namun Zaid mencoba kuat menjalarinya, meski sadar tak semua mampu Ia gapai. Selalu khawatir dengan suatu saatku yang membuatnya sulit melangkah. Lalu dia, aku, dan harapan itu selayak dua dahan di pinggir pantai yang maha luas lautnya. Dia dan aku adalah dua dahan yang terpisah oleh air dan akar-akar kecil. Sementara harapan adalah lautan, yang tak mungkin ditumbuhi dahan di dalamnya. Sebab itu, ia ingin tetap denganku.
“Biarkan Aku tetap untuk berbakti, Ayah. Bukankah surga itu lebih indah dari Danube?”
Kemudian, aku beranjak tanpa menghirau bola matanya. Tak jua tersimpul kecewa atau bahagia.
Penulis adalah Radhia Humaira mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah yang juga aktif di UKM Pers DETaK Unsyiah sejak 2015.
Editor: Dinda Triani